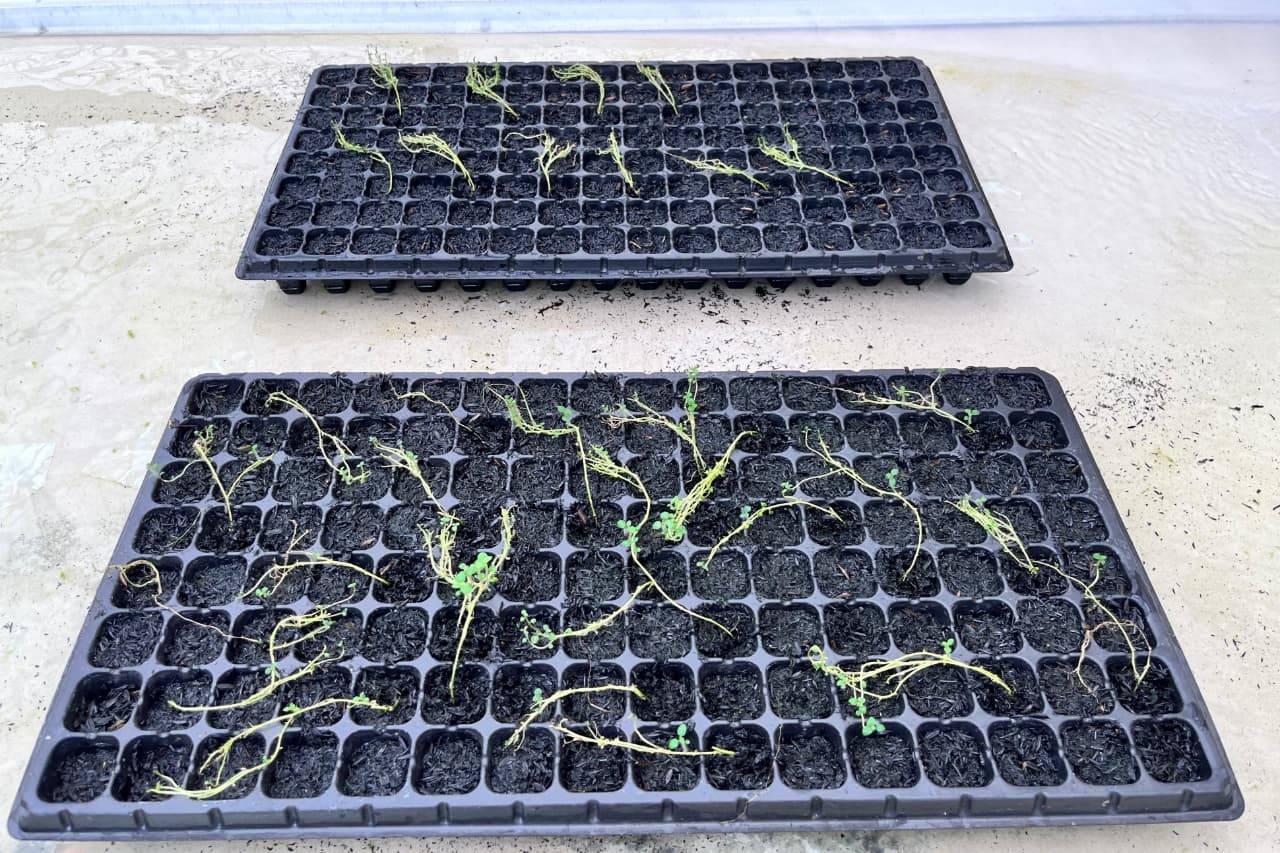MENATA KEBERADAAN SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN
 Dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tersirat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian masih terbatas pada kegiatan penyuluhan sebagai kegiatan pendidikan (non formal), belum sebagai kegiatan pemberdayaan.Sedangkan penyuluhan pertanian sendiri sebenarnya sebagai salah satu upaya pemberdayaan petani dan keluarganya agar mereka mau, mampu dan sanggup mandiri dalam mengelola usahanya dengan produktif, efektif, dan efisien serta berdayasaing tinggi. Petani yang berdayasaing tinggi adalah petani yang tingkat produktifitas, efektifitas dan efesiensi usahanya tinggi serta kualitas hasil sesuai dengan permintaan pasar, sehingga produknya mampu bersaing di pasar, baik pasar domestic, regional, maupun pasar global.
Dalam UU Nomor 16 Tahun 2006 tersirat bahwa kegiatan penyuluhan pertanian masih terbatas pada kegiatan penyuluhan sebagai kegiatan pendidikan (non formal), belum sebagai kegiatan pemberdayaan.Sedangkan penyuluhan pertanian sendiri sebenarnya sebagai salah satu upaya pemberdayaan petani dan keluarganya agar mereka mau, mampu dan sanggup mandiri dalam mengelola usahanya dengan produktif, efektif, dan efisien serta berdayasaing tinggi. Petani yang berdayasaing tinggi adalah petani yang tingkat produktifitas, efektifitas dan efesiensi usahanya tinggi serta kualitas hasil sesuai dengan permintaan pasar, sehingga produknya mampu bersaing di pasar, baik pasar domestic, regional, maupun pasar global.
Upaya menata kembali penyuluhan pertanian masa depan akan mencakup: konsep dasar penyuluhan pertanian, dukungan politik (political will), pendekatan, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, materi penyuluhan, pembiayaan, pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan, yang semuanya dilaksanakan secara simultan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 juga menyatakan bahwasystem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mendefinisikan penyuluhan pertanian sebagai proses pembelajaran bagi pelaku utama serata pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Sehingga beberapa sumber menyatakan bahwa penyuluhan pertanian bukan hanya mencakup kegiatan pendidikan non formal, tetapi kegiatan pembelajaran, dapat dilihat dari kegiatan pokok penyuluhan pertanian, yaitu; (1). Menyampaikan informasi budidaya/teknik produksi, social, ekonomi dan manajemen kepada petani dan keluarganya, (2). Memfasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya, (3). Memberikan rekomendasi dan mengihtiarkan akses petani dan keluarganya ke sumber-sumber informasi dan sumberdaya yang mereka butuhkan untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi (4). Menumbuh kembangkan kelembagaan petani menjadi lembaga social ekonomi yang tangguh sebagai bagian dari system usaha mereka (5). Mendorong terjalinnya kerjasama antara petani dengan stakeholders yang saling menguntungkan. (6). Menjadi kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai lembaga mediasi yang menyangkut penggunaan teknologi dan kepentingan petani lainnya dan (7). Membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan petani.
Dimensi pemberdayaan adalah partisifasi dan kemandirian. Partisifasi adalah keterlibatan atau peran seseorang secara penuh dalam setiap langkah dan tindakan mengambil keputusan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan. Sedangkan kemandirian adalah kemampuan untuk meningkatkan, mempertahankan dan mengelola berbagai kegiatan, kelembagaan, potensi dan sumberdaya lain yang dimiliki tanpa menggantungkan sepenuhnya pada pihak lain.
 Penyuluhan pertanian ke depan harus di dukung oleh political will dan komitmen yang kuat dari pemerintah, mulai dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Political will ini pada dasarnya sudah ada dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tantang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K). Sedangkan untuk memperkuat komitmennya pemerintah harus mensosialisasikan Undang-undang ini dengan menjelaskan pasal-pasal yang menunjukan adanya political will dan komitmen pemerintah, seperti kesediaan pemerintah (pusat dan daerah) untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kegiatan lain adalah pemerintah harus menjelaskan kepada seluruh aparat baik di pusat maupun di daerah bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum adalah hak asasi warga Negara Republik Indonesia (UU Nomor 16 Tahun 2006, Menimbang (a)). Pasal-pasal lain yang juga harus membicarakan dengan intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mengenai pembentukan kelembagaan penyuluh pertanian pengangkatan dan penugasan tenaga penyuluh PNS, pembiayaan dan pengadaan sarana prasarana penyuluhan yang dibutuhkan).
Penyuluhan pertanian ke depan harus di dukung oleh political will dan komitmen yang kuat dari pemerintah, mulai dari pusat, provinsi sampai ke kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Political will ini pada dasarnya sudah ada dalam bentuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tantang system penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (SP3K). Sedangkan untuk memperkuat komitmennya pemerintah harus mensosialisasikan Undang-undang ini dengan menjelaskan pasal-pasal yang menunjukan adanya political will dan komitmen pemerintah, seperti kesediaan pemerintah (pusat dan daerah) untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Kegiatan lain adalah pemerintah harus menjelaskan kepada seluruh aparat baik di pusat maupun di daerah bahwa penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum adalah hak asasi warga Negara Republik Indonesia (UU Nomor 16 Tahun 2006, Menimbang (a)). Pasal-pasal lain yang juga harus membicarakan dengan intensif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mengenai pembentukan kelembagaan penyuluh pertanian pengangkatan dan penugasan tenaga penyuluh PNS, pembiayaan dan pengadaan sarana prasarana penyuluhan yang dibutuhkan).
Pendekatan penyuluhan pertanian ke depan adalah gabungan dari beberapa pendekatan penyuluhan. Mengacu kepada pendekatan penyuluhan yang dikembangkan oleh Rivera (2001), pendekatan penyuluhan di Indonesia merupakan gabungan dari; (1) pendekatan partisifatif (the agricultural extension participatory approach), (2) pendekatan pengembangan sisitem usaha tani (the farming system development approach), (3) pendekatan patungan biaya (the cost sharing approach) dan (4) pendekatan latihan dan kunjungan (the training and visit approach). Untuk pengembangan komoditi pertanian unggulan tertentu, digunakan juga pendekatan komoditi unggulan (the commodity specialize approach).
Ukuran keberhasilan pendekatan penyuluhan partisifatif adalah jumlah petani yang terlibat secara aktif dalam perencanaan penyuluhan, pelaksanaan, evaluasi dan mengambil manfaat (benefiting) secara terus menerus dari kegiatan penyuluhan pertanian. Sedangkan ukuran keberhasilan pendakatan pengembangan usaha tani adalah tingkat penerapan teknologi oleh petani yang dikembangkan oleh program pengembangan usaha tani tersebut. Pendekatan patungan biaya, ukuran keberhasilannya adalah kemauan dan kemampuan petani untuk patungan biaya, baik secara individual maupun melalui unit pemerintahan local, untuk biaya penyelenggaraan penyuluhan. Patungan biaya ini juga diharapkan dari kontribusi pihak swasta.
Pendekatan Pelatihan dan Kunjungan yang dulu dikenal dengan system LAKU yang merupakan Sistem Kerja Penyuluh Pertanian. Pendekatan LAKU ini pada penyuluhan pertanian masa depan perlu dimodifikasi. Kunjungan ke petani/kelompok tani tidak lagi ditetapkan secara ketat, yaitu 2 minggu sekali, tetapi disesuaikan secara regular tetapi dilaksanakan dengan prinsip; petani yang banyak masalahnya akan lebih sering dikunjungi. Masalah yang dihadapi petani/kelompoktani dapat diketahui dengan melihat Programa Penyuluhan Pertanian yang disusun oleh Balai Penyuluhan (BP)/Unit Pelayanan Teknis (UPT) dan atau oleh Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan. Sedangkan waktu kunjungan disesuaikan dengan rencana kerja yang disusun oleh penyuluh pertanian di BP/UPT. Untuk kegiatan latihannya tetap dilakukan 2 minggu sekali. Latihan ini sekaligus digunakan untuk mendiskusikan perkembangan yang terjadi di lapangan. Ukuran keberhasilan pendekatan LAKU adalah meningkatnya produksi komoditi (crops) tertentu sesuai dengan yang diprogramkan. Sedangkan untuk pendekatan komoditi unggulan, ukuran keberhasilannya adalah total produksi dan mayoritas keterlibatan perekonomian dari komoditi tertentu yang diprogramkan.
Dengan gabungan pendekatan ini, maka keberhasilan penyuluhan pertanian tidak hanya diukur dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan, tetapi juga berapa besar keterlibatan petani dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sharing biaya serta berapa besar manfaat yang diperoleh petani dari keikutsertaannya dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Ukuran keberhasilan penyuluhan yang lain dikemukakan oleh Padmanegara (1974) dan Slamet (1987) dua pakar penyuluhan pertanian ini menyatakan bahwa ukuran keberhasilan penyuluhan pertanian adalah perubahan prilaku positif pada diri petani dan keluarganya. Selanjutnya menurut Slamet (1997), perubahan prilaku tersebut biasanya berupa; (1). Perubahan dalam pengetahuan, atau hal yang diketahui, (2). Perubahan dalam keterampilan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu dan (3). Perubahan dalam sikap mental atau segala sesuatu yang dirasakan.
Melihat begitu besarnya jumlah petani di Indonesia yang harus dilayani, diperlukan kelembagaan yang akan merencanakan, mengelola, mengembangkan dan membiayai penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Pengalaman membuktikan bahwa ketika UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (otonomi daerah) diberlakukan, hampir semua pemerintah kabupaten/kota membubarkan kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota termasuk kelembagaan penyuluhan di tingkat kecamatan, sehingga kegiatan penyuluhan pertanian mengalami stagnasi.
 Dengan keluarnya UU Nomor 16 tahun 2006, beberapa Pemerintah Kabupaten/kota kembali membentuk kelembagaan penyuluh pertanian. Sampai dengan bulan Agustus 2011 dari 497 kabupaten/kota, baru 154 kabupaten/kota yang membentuk kembali kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota dan baru 4880 dari 6694 kecamatan yang membentuk kembali Balai Penyuluhan (dahulu Balai Penyuluhan Pertanian = BPP) dan belum ada Pos Penyuluhan yang diberdayakan. Untuk itu Pemerintah Pusat harus membicarakan secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota yang belum membentuk kembali kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota dan kecamatan, untuk kembali membentuk kelembagaan-kelembagaan penyuluhan tersebut. Pemerintah kabupaten/kota juga harus segera mendorong terbentuknya Pos Penyuluhan Desa/kelurahan dan memberdayakannya.
Dengan keluarnya UU Nomor 16 tahun 2006, beberapa Pemerintah Kabupaten/kota kembali membentuk kelembagaan penyuluh pertanian. Sampai dengan bulan Agustus 2011 dari 497 kabupaten/kota, baru 154 kabupaten/kota yang membentuk kembali kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota dan baru 4880 dari 6694 kecamatan yang membentuk kembali Balai Penyuluhan (dahulu Balai Penyuluhan Pertanian = BPP) dan belum ada Pos Penyuluhan yang diberdayakan. Untuk itu Pemerintah Pusat harus membicarakan secara intensif dengan pemerintah kabupaten/kota yang belum membentuk kembali kelembagaan penyuluhan kabupaten/kota dan kecamatan, untuk kembali membentuk kelembagaan-kelembagaan penyuluhan tersebut. Pemerintah kabupaten/kota juga harus segera mendorong terbentuknya Pos Penyuluhan Desa/kelurahan dan memberdayakannya.
Dalam menyelenggarakan dan mengembangkan penyuluhan di kabupaten/kota, Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota juga harus dapat menggantikan salah satu fungsi Balai Informasi Pertanian (BIP), yaitu memilih dan mengelola data informasi, untuk kemudian diformat sebagai materi penyuluhan dan dikemas dalam bentuk media penyuluhan dan akhirnya diperbanyak dan disebarkan ke Balai Penyuluhan dan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagai pengguna informasi pertanian tersebut. Upaya penyediaan dan pelayanan informasi pertanian dalam format materi penyuluhan dan dikemas dalam bentuk media penyuluhan dilakukan melalui: (1). Membangun prasarana dan saran pelayanan informasi pertanian dengan penggunaan peralatan mutakhir (ICT) (2). Mengembangkan jejaring penyediaan informasi pertanian, (3). Penyediaan informasi pertanian dengan memanfaatkan multi media menggunakan information and communication technology (ICT), (4). Peningkatan ketersediaan sarana untuk mengembangkan media-media penyuluhan (5). Meningkatkan kemampuan petugas yang melayani penyediaan dan penyebaran informasi pertanian, (6). Optimalisasi pemanfaatan unit informasi pertanian dan teknologi yang tersedia (7). Membuat program khusus penyediaan dan penyebaran informasi pertanian yang dibutuhkan petani (8). Mengalokasikan anggaran khusus di lembaga penyuluhan Pemerintah (Pusat), provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
Daftar Pustaka
FAO, 2001. Agricultural and Rural Extension Worldwide : Option for institutional Reform in Developing Countries, Prepared by Rivera, Wiliam M, In Collaboration with Qomar M Kalim and Van Crowder, Extention Education and Communication Service, Research, Extension and Training Division, Sustainable Development Departement, Rome November 2001
Nasution Zulkarimen, 2002 Komunikasi Pembangunan. Pengenalan Teori dan Prakteknya. Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
Ndraha Thaliziduhu, 1999. Pengantar Teori Pengembangan Sumberdaya Manusia. Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
Padmanegara Salmon. 1974. Membina Penyuluhan Pertanian. Dicetak ulang oleh Departemen Pertanian, 1984.
Slamet Margono, 1987. Memantapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia. Dalam Yustina Ida dan Sudradjat Adjat. Membentuk Pola Prilaku Manusia Pembangunan. IPB Press, Bogor, 2003.